
Oleh Munawar M. Saad
DALAM minggu ini Walikota Singkawang dan jajaran pemerintahannya dihadapkan pada persoalan penolakan pembangunan patung naga. Sebahagian masyarakat Kota Singkawang dari FPI, FPM dan Aliansi LSM Perintis pada tanggal 5 Desember 2008 turun ke jalan memprotes pembangunan patung naga di jalan Kempol Machmud-Niaga Kota Singkawang. Alasan penolakan karena pembangunan patung naga bukan untuk kepentingan umum, namun hanya untuk kepentingan etnis tertentu.Kasus penolakan pembangunan patung naga di Kota Singkawang tersebut tidak boleh kita anggap sepele dan bahkan ada kecenderungan untuk menyederhanakan persoalan. Akan tetapi patut kiranya kita cari akar persoalannya. Mengapa warga tidak setuju terhadap simbol-simbol yang bernuansa etnis. Apakah peristiwa tersebut pertanda adanya ketersinggungan sekelompok warga terhadap warga dari etnis tertentu pasca pilwako?
Dari peristiwa yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa persoalan etnis di daerah ini masih cukup rawan. Bila terjadi sedikit gejolak di masyarakat, akan patal akibatnya. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus niscaya akan dapat menggorogoti dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa, baik secara politik maupun sosial budaya.
Heterogenitas masyarakat di Kalimantan Barat memang potensial sebagai ladang konflik sebagaimana yang pernah diprediksikan sebelumnya oleh Samuel Huntington sebagai “Benturan Peradaban/The Clash of Civilizations” yaitu etnik, agama dan peradaban. Tingkat kesejahteraan penduduk yang kebanyakan masih rendah, ketimpangan struktur sosial kemasyarakatan, kesempatan kerja dan hak-hak kepemilikan juga menyebabkan pengentalan-pengentalan konflik di tengah-tengah realitas kehidupan keseharian masyarakat kita (Syarif Ibrahim Alqadrie, 1999; Bakran Suni, 2000). Begitu juga dengan tingkat pendidikannya, dapat dijadikan alasan terjadinya konflik horizontal.
Pembangunan sosial budaya selayaknya mengandung arti sebagai proses akulturasi dikarenakan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat guna menuju kondisi yang lebih baik. Perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat dan kedaerahan seharusnya tidak menjadikan suatu daerah yang majemuk jatuh ke dalam ketegangan budaya karena merupakan ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk –suatu istilah yang pertama sekali diperkenalkan oleh Furnivall (Nasikun, 1993:23).
Dalam masyarakat yang majemuk menjadi sulit dipahami norma yang berbeda-beda yang menjadi dasar kehidupan sub kelompok yang berbeda-beda itu. Interaksi sosial antar penduduk dengan kemajemukan tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah SARA dan sekaligus mendorong masing-masing pihak memperkuat identitas suku dan ikatan primordialnya.
Penulis tidak bermaksud berspekulasi dan mengandai-andai, namun semata-mata ingin berbagi pemikiran demi terwujudnya Singkawang kota yang damai, aman, sejuk dan sejahtera. Belajar dari kasus patung naga di Kota Singkawang, penulis ingin kita bersama-sama mengangkat permasalahan pentingnya memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk. Mengapa tema itu diangkat, mengingat di wilayah kita ini sering terjadi pertikaian horizontal akibat menajamnya berbagai perbedaan, baik perbedaan suku, golongan, status sosial maupun perbedaan agama. Perbedaan selama ini selalu menjadi masalah (problematik), padahal yang sebenarnya perbedaan itu adalah anugerah yang seharusnya menjadi modal sosial dalam membangun masyarakat. Untuk itu penulis mencoba menuangkan beberapa pikiran seputar bagaimana menjaga semangat multikulturalisme pada masyarakat. Ada dua komitmen penting yang harus dipegang oleh masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan damai dalam suatu masyarakat yang beraneka ragam kultur, etnik, agama dan keyakinan, yaitu sikap pluralisme dan inklusifisme.
Pengertian pluralisme dan inklusivisme memang tidak jauh berbeda. Pengertian pluralisme adalah bahwa tiap orang/warga dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak warga/orang lain, tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebhinnekaan. Sedangkan inklusifisme adalah sikap keterbukaan dalam bergaul sesama warga masyarakat (memahami orang lain. Pluralisme tidak semata menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Namun yang dimaksud adalah keterlibatan aktif terhadap kenyataan kemajemukan tersebut.
Indonesia dibangun atas dasar perbedaan dari berbagai sisi, seperti perbedaan suku, agama dan ras. Melalui bhinneka tunggal ika itulah terbangun kebersamaan untuk mencapai sebuah tujuan berbangsa dan bernegara dengan tetap harmonis dan bergandengan tangan. Kondisi Indonesia sejak awal pembentukannya adalah masyarakat multikultural yang unik. Namun ironisnyanya sejak lama negara (state) belum memberikan kesempatan belajar hidup bersama dalam perbedaan kepada bangsanya sehingga tidak terjadi dialog budaya yang dinamis dan terbuka (Chairil Effendi).
Menyikapi kondisi Kalimantan Barat yang masyarakatnya pluralistik secara antropologis, historis dan sosiologis sehingga perlu penanganan khusus dan penuh kehati-hatian dalam proses pembinaan warganya agar dapat hidup secara harmonis, jangan sampai muncul semangat superioritas etnis. Jika boleh dianalogikan bahwa kondisi di Kalimantan Barat yang multi etnik dan agama seperti beberapa ekor ayam jago yang kuat dan bertaji hidup dalam satu kandang (sangkar). Apabila sang empunya ayam jago tersebut tidak arif dan bijak dalam memberikan pelayanan atau perlakuan boleh jadi ayam-ayam tersebut satu saat akan berkelahi dan bertarung.
Menurut beberapa sumber yang penulis baca bahwa multikulturalisme di Kalimantan Barat saat ini mengalami problema tersendiri yang perlu diwaspadai. Problema dimaksud antara lain :
• Indeks pembangunan manusia bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berada pada urutan bawah sehingga masyarakatnya terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan.
• Nilai-nilai masyarakat Kalimantan Barat sudah tercabik-cabik sejalan dengan hancurnya habitat kebudayaan mereka,
• Struktur mental sebagian kelompok masyarakat mengalami kegoncangan akibat konflik sosial yang terjadi beberapa kali.
• Masyarakat hidup terkotak-kotak dan berusaha membangun sandaran hukum baru sehingga terjadi dualisme hukum.
Pembauran masyarakat antara berbagai etnis di suatu wilayah merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat majemuk (plural). Tanpa adanya proses pembauran masyarakat, konflik horizontal akan dengan mudah tersulut, walau hanya dengan sumber pemicu yang sangat sederhana. Dari berbagai kasus kerusuhan (konflik horizontal) yang pernah terjadi di wilayah Kalimantan Barat ini mengindikasikan akan pentingnya pembauran tersebut.
Dalam merajut nilai persaudaraan di masyarakat mengharuskan setiap warga masyarakatnya untuk hidup saling berdampingan, tanpa memisahkan diri dari suatu komunitas masyarakatnya dan membentuk komunitas tersendiri, meskipun dalam hidup keseharian di masyarakat selalu mengadakan hubungan/kontak sosial dengan masyarakat lainnya. Hidup berkelompok cenderung akan menyebabkan hegemoni kelompok, dan hal ini akan dengan mudah mengundang konflik.
Selain itu, “kerelaan” untuk menjunjung tinggi nilai-nilai, adat istiadat dan budaya yang berkembang di suatu masyarakat menjadi suatu keniscayaan dalam proses pembauran masyarakat. Atau dengan lain perkataan, kepandaian beradaptasi dan berasimilasi dengan masyarakat tempatan atau “pandai membawa diri” menjadi persyaratan mutlak bagi para warga masyarakat agar dapat diterima dengan baik oleh warga lain.
Kepada para tokoh agama dan masyarakat dari berbagai etnik, agar senantiasa secara intensif mengadakan pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi guna menemukan jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, dan segera mensosialisasikan hasilnya kepada komunitasnya masing-masing dengan sebenar-benarnya sehingga tidak akan menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah sebaiknya mencoba merentas jalan keluar dan alternatif pernyelesaian yang lain, seperti mengadakan pertemuan antar warga masyarakat dalam suatu wilayah atau daerah kecamatan, tanpa adanya upaya pendelegasian, dan pemerintah hanya sebagai mediator dan fasilitatornya. Untuk hidup berdampingan dalam masyarakat mengisyaratkan adanya keinginan dan kerelaan dari etnik tertentu agar mau merubah segala sifat, sikap, perilaku dan budaya asal dengan menyesuaikan diri dengan perilaku masyarakat sekitarnya. SALAM DAMAI.
(Penulis adalah dosen Jurusan Dakwah pada STAIN Pontianak)
















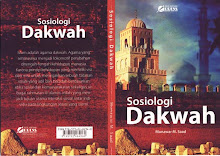

1 komentar:
Mohon maaf pa saya bertanya apakah bapak yang menulis buku sosiologi dakwah? mohon e-mail bapak!
Posting Komentar